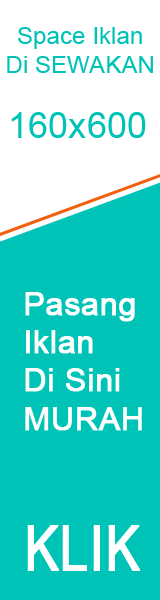ELTV SATU ||| CERPEN – Maya duduk di sudut sebuah taman kecil di kota asing yang tak pernah benar-benar memeluknya. Bangku kayu itu sudah menjadi tempatnya setiap sore—tempat sunyi yang ia datangi seperti ritual, seakan hanya di sanalah seluruh beban yang ia bawa dari negeri jauh bisa jatuh perlahan. Angin membawa suara kendaraan dan bahasa yang belum sepenuhnya ia pahami, tetapi kesunyian tetap menang. Di sanalah Maya menatap dunia dari kejauhan, sambil menatap dirinya sendiri dari jarak yang lebih dalam.
“Kenapa aku selalu kembali ke sini?” batinnya bertanya. “Apa aku sedang lari… atau sedang mencari sesuatu?”
Kesepian kota asing itu menjadi cermin yang memantulkan kegundahan yang selama ini ia sembunyikan. Setiap kali ia duduk, resahnya muncul tanpa malu, seolah menunggu sejak pagi untuk akhirnya bicara.
“Maya, kau tak benar-benar kuat selama ini. Kau hanya pandai diam,” suara batinnya kembali menyentil.
“Benarkah? Atau mungkin aku memang harus kembali diam agar bisa mendengar diriku sendiri?”
Ia memeluk tas kecil di pangkuannya, menatap orang-orang yang lewat dengan wajah yang punya tujuan—sesuatu yang ia rasa hilang beberapa tahun terakhir. Di ruang sepi itu, Maya belajar bahwa gundah bukan musuh. Ia hanyalah pesan, ketukan halus yang mengajak seseorang membuka pintu dirinya sendiri.
“Apa yang sebenarnya aku takutkan?” pikirnya. “Kembali pulang? Atau tetap tinggal di sini, dengan semua ketidakpastian?”
Setiap hari ia kembali ke tempat yang sama karena hanya di sanalah ia bisa mendengar gemuruh yang ia sembunyikan dari dunia. Tempat itu bukan pelarian. Ia tahu itu. Setiap langkah menuju bangku tua itu adalah keberanian kecil, meski sering berbalut air mata yang tidak pernah turun.
“Kalau aku jujur… aku rapuh,” Maya berbisik dalam hati.
“Tapi bukankah dari rapuh itu aku belajar berdiri lagi?”
Ia menatap langit asing yang mulai berubah warna. Gundah tak hilang oleh keramaian; karena itu ia memilih sepi. Kesunyian menamparnya, tetapi juga merangkulnya. Seperti guru yang keras namun jujur. Dan dalam diam itu, Maya perlahan mengerti bahwa perasaan resah bukanlah kutukan, melainkan panggilan untuk berubah.
“Aku tidak sendiri,” ia meyakinkan dirinya. “Aku hanya sedang tumbuh, dan tumbuh memang menyakitkan.”
Kesepian, gundah, dan resah yang selama ini mengikutinya ternyata membentuk sesuatu yang baru keberanian yang selama ini ia kira hilang. Tempat sepi itu menjadi laboratorium jiwanya. Di sana, Maya memahami lukanya, menata ulang pikirannya, dan memandang masa depannya dengan mata yang sedikit lebih jernih.
Saat ia bangkit dari bangku itu, ia tahu satu hal: meskipun ia jauh dari negeri sendiri, ia sedang dalam perjalanan pulang bukan pulang ke tempat, tetapi pulang kepada dirinya sendiri. (***)